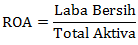BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Masalah umum yang sering dihadapi negara berkembang seperti Indonesia adalah inflasi. Di Indonesia, laju inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen sampai tahun 2005 selalu lebih dari 5% kecuali pada tahun 1985 sebesar 4,3%. Bahkan empat tahun terakhir dari tahun 2003 sampai dengan 2006 besarnya adalah 6,8%, 6,06%, 10,4% dan 14,8%. Ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara langsung dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat dan perubahan biaya produksi atau fator-faktor produksi. Walaupun angka inflasi tersebut dibawah dua digit, namun inflasi di atas 5% saja sudah cukup tinggi, apalagi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan penduduk.
Secara umum Laporan Keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost accounting). Dengan prinsip ini laporan keuangan disusun menggunakan harga-harga yang timbul dari transaksi. Sebagai alat pengukur/pertukaran di dalam perekonomian digunakan satuan unit moneter. Kondisi inflasi menyebabkan satuan unit moneter menjadi tidak stabil. Sehingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli.
Oleh karena itu muncul ide menggunakan model akuntansi bukan historis lainnya seperti current value accounting, replacement value accounting, net realizable value accounting yang berbeda dari akuntansi biaya historis. Dalam
akuntansi inflasi dapat digunakan dua alternative pengukuran, yaitu bisa dengan
metode akuntansi saat ini atau dengan metode tingkat harga umum.
Metode
akuntansi nilai saat ini mencerminkan perubahan-perubahan yang terjadi pada
tingkat harga khusus, tingkat harga umum mencerminkan perubahan-perubahan yang
terjadi pada tingkat harga umum. Metode
tingkat harga umum dinyatakan pada postulat satuan moneter yang stabil. Motode ini menyesuaikan laporan keuangan di
masa inflasi dengan penyajian kembali laporan keuangan biaya historis yang
dibuat sesuai dengan tingkat daya beli umum. Dengan menyajikan kembali laporan keuangan (akuntansi biaya historis)
yang dibuat sesuai dengan tingkat daya beli umum, maka akan tersusun laporan
keuangan yang bisa relevan dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, khususnya
pada masa inflasi.
Perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna merupakan perusahaan rokok terkemuka dan salah satu tertua di Indonesia. Sejarah dan sukses Sampoerna tidak dapat dipisahkan dari sejarah keluarga Sampoerna sebagai pendirinya. Pada tanggal 18 Mei 2005, PT HM Sampoerna melakukan akuisisi dengan Philip Morns Internasional sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia. Pada akhir tahun 2010, jumlah karyawan PT HM Sampoerna dan anak perusahaannya mencapai sekitar 27.600 orang. Perseroan mengoperasikan enam pabrik rokok di Indonesia. Selain hal tersebut, PT HM Sampoerna mendirikan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK Sampoerna) yang merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian setempat.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "PENERAPAN GENERAL PRICE LEVEL ACCOUNTING (GPLA) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT HM. SAMPOERNA Tbk PERIODE 2010"
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana kewajaran laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk periode 31 Desember 2010 setelah disesuaikan dengan menggunakan metode General Price Level Accounting (GPLA).
1.3 Batasan Masalah
Pada penulisan ini penulis membatasi masalah yaitu hanya menganalisa pengaruh akuntansi inflasi metode tingkat harga secara umum pada laporan keuangan PT HM. Sampoerna Tbk yaitu Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi periode Desember 2010. Asumsi peneliti menggunakan metoda tingkat harga umum adalah di samping kendala perolehan data, peneliti berasumsi bahwa dengan menggunakan metoda tingkat harga umum, nilai harta, hutang dan modal yang terpengaruh oleh perubahan harga disesuaikan dengan faktor indeks harga, sehingga dinyatakan dengan nilai uang yang sama.
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk meganalisa kewajaran dan membandingkan penyajian laporan keuangan PT HM. Sampoerna Tbk periode 31 Desember 2010 berdasarkan metode General Price Level Accounting (GPLA).
1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:
- Manfaat akademis, yaitu: sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis ataupun memperdalam penelitian ini.
- Manfaat Praktis, yaitu untuk sebagai bahan pertimangan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan non-konvensional.
1.6 Kerangka Pemikiran
Laporan keuangan yang didasarkan pada nilai historis (historical cost accounting) yaitu menggunakan harga pada saat transaksi dan menganggap bahwa harga-harga akan stabil. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan tingkat harga umum (general price level accounting) yang mampu memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya atau tidak, mendekati keadaan yang sebenarnya dan juga mampu memberikan nilai sesungguhnya dari rupiah (daya beli rupiah).
Penelitian yang dilakukan oleh Kery Soetjipto (2000) dan Iven Susanto dan Ivonne Moniaga F. P (2002) memberikan kesimpulan bahwa adanya perbedaan antara nilai historis (historical cost accounting) dengan nilai berdasarkan tingkat harga umum. Namun, dan keduanya juga didapatkan adanya perbedaan dalam hal perlu tidaknya dilakukan penyesuaian laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Akuntansi Inflasi
2.1.1 Pengertian Akuntansi Inflasi
Banyak studi mengenai inflasi di Negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri misalnya memburuknya term of trade, utang luar negeri dan kurs valuta asing dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.
Menurut Naim (2001:7) Akuntansi Inflasi merupakan suatu proses akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan tingkat perubahan harga, sehingga informasi yang dihasilkan menunjukkan ukuran satu mata uang dengan tingkat harga yang berlaku. Ada beberapa pendekatan untuk menyajikan informasi tersebut antara lain pendekatan harga umum (general price level), pendekatan biaya berlaku (current cost), dan gabungan kedua pendekatan tersebut.
General Price Level Accounting atau dikenal sebagai akuntansi tingkat harga umum menyatakan bahwa nilai sesungguhnya dari rupiah ditentukan oleh barang atau jasa yang diperoleh, yang biasa disebut daya beli. Akuntansi tingkat harga umum akan mengadakan penyajian kembali komponen-komponen laporan keuangan kedalam rupiah pada tingkat daya beli yang sama, namun sama sekali tidak mengubah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi berdasarkan nilai historis. Akuntansi penyusutan saat ini merupakan suatu upaya untuk menyediakan lebih realistis nilai buku dengan menilai asset sebesar biaya pengganti saat ini, bukan jumlah yang harus dibayar. Biaya saati ini (current cost) biasanya dihitung dengan menyesuaikan nilai historis untuk masa inflasi, selain penyesuaian seperti penyusutan.
2.1.2 Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga
Laporan keuangan yang disajikan oleh proses akuntansi keuangan (menurut Standar Akuntansi Keuangan) adalah bersifat umum. Laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip harga perolehan (cost) historis yang mengasumsikan bahwa harga-harga (unit moneter) adalah stabil. Ada dua persoalan yang dihadapi oleh akuntansi yang mendasarkan pada historical cost pada saat terjadi inflasi, yaitu:
- Persoalan Penilaian (Valuation Problem) Nilai aktiva individual akan berubah jika dibandingkan dengan aktiva lain, merupakan daya beli uang tidak berubah. Dapat juga perubahan itu disesabkan oleh perubahan persepsi orang terhadap manfaat barang tertentu akan berubah, sehingga akan mempengaruhi nilai barang tersebut.
- Persoalan Unit Pengukur (Measurement Unit Problem) Karena adanya inflasi, daya beli berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogen lagi jika dikaitkan dengan waktu.
Pada kenyataannya, harga selalu berubah, cenderung semakin naik atau yang disebut dengan inflasi. Sehingga tanah yang dibeli atau diperoleh tahun 2000 sebesar Rp 100.000.000,00 tidak sama nilainya dengan tahun 2008. Melihat keadaan seperti ini profesi akuntansi mengganggap bahwa dalam penentuan nilai aktiva dengan mengakumulasi harga perolehan aktiva pada waktu yang berbeda kurang tepat, karena harga perolehan aktiva tersebut tidak dapat diperbandingkan, sehingga diperlukan adanya penyesuaian untuk menyatakan nilai perolehan aktiva tersebut menurut nilai uang yang konstan agar dapat diperbandingkan.
2.1.3 Pendekatan Akuntansi Inflasi
Menurut Sari (2009) untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan penyajian informasi keuangan berkaitan dengan adanya perubahan harga ini. Ada beberapa konsep penyajian informasi keuangan, yaitu:
- Konsep Akuntansi Nilai Uang Konstan
- Konsep Harga Perolehan Sekarang (Current Cost Accounting)
- Konsep Gabungan Harga Perolehan Sekarang dan Nilai uang Konstan
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil pendekatan Akuntansi Inflasi Konsep Akuntansi Nilai uang Konstan dengan menggunakan Metode Tingkat Harga Umum (General Price Level Accounting).
2.1.4 Konsep Akuntansi Tingkat Harga Umum
Menurut Sari (2009) tujuan konsep ini adalah menyajikan informasi tentang akibat perubahan harga terhadap suatu usaha perusahaan, informasi seperti ini berguna bagi manajemen dalam melakukan penilaian terhadap kemuajan usaha perusahaan karena unit moneter yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan unit moneer yang mempunyai daya beli sama. Akuntansi tingkat harga umum akan mengadakan enyajian kembali komponen-komponen laporan keuangan ke dalam rupiah pada tingkat daya beli yang sama, namun sama sekali tidak mengubah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi berdasarkan nilai historis.
Penyesuaian atas besaran keuangan untuk inflasi guna mencerminkan nilai hrga umum atau tingkat harga umum dan penggunaan nilai yang telah disesuaikan tersebut dalam akuntansi dengan menggunakan indeks harga. Indeks harga yang biasa digunakan adalah indeks harga konsumen, yaitu suatu indeks yang menyajikan perubahan periodik dalam biaya kelompok barang-barang terpilih yang dibeli konsumen yang digunakan sebagai ukuran inflasi.
Dalam penyusunan berdasarkan tingkat harga umum perlu diperhatikan pos-pos yang akan terpengaruh dengan adanya penurunan daya beli rupiah, yaitu:
- Monetary Assets, seperti kas ditangan, surat-surat berharga, piutang dan lain-lain yang sifatnya sebagai dormant account akan mengalami penurunan daya beli secara berarti karena rekening-rekening tersebut tidak dapat lagi dinilai.
- Non Monetary Assets, secara rill tidak mengalami penurunan daya eli, tetapi dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena pengaruh penurunan harga beli, tetapi dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena pengaruh penurunan harga beli.
- Assents dalam bentuk valuta asing tidak dipengaruhi oleh penurunan daya beli rupiah karena dapat dinilai dengan kurs yang terakhir.
2.1.5 Metode Penyajian Nilai Aktiva Menurut Konsep Harga Konstan
Tahap-tahap untuk menyajikan nilai aktiva menurut nilai sekarang (Current Cost), adalah sebagai berikut:
- Mendapatkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan harga perolehan historis.
- Menentukan dan mendapatkan satu indeks tingkat harga umum yang akan digunakan penyesuaian.
- Mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan menurut pos-pos moneter dan pos-pos non moneter.
- Menyesuaikan pos-pos non-moneter dengan faktor konversi indeks harga, untuk menyatakan nilai aktiva dengan nilai uang menurut harga yang berlaku sekarang.
- Menghitung keuntungan dan kerugian tingkat daya beli umum (tingkat harga umum) yang muncul dari kepemilikan atas pos-pos moneter.
2.1.6 Perlakuan Terhadap Pos-pos Moneter
Pos-pos moneter, seperti telah disebutkan diatas, merupakan pos-pos yang jumlahnya tetap, dan nilainya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai uang mata uang karena ditentukan oleh kntrak. Meskipun jumlah-jumlah ini tetap, nilai dari pos-pos moneter dilihat dari segi daya beli mengalami perubahan. Pemilik pos-pos moneter, karenanya mengalami keuntungan atau kerugian daya beli karena terjadi perubahan pada tingkat harga umum. Keuntungan dan kerugian seperti ini disebut keuntungan atau kerugian tingkat daya beli umum, atau keuntungan tingkat harga umum atau kerugian akibat pos-pos moneter. Lebih khusus lagi, selama periode harga-harga mengalami kenaikan:
- Aktiva moneter kehilangan daya beli, yang akan diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum.
- Kewajiban moneer mendapatkan daya beli, yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum.
Selama periode di mana harga-harga mengalami penurunan:
- Aktiva moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum.
- Kewajiban moneter kehilangan daya beli, yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum.
Laba atau rugi tingkat harga umum dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
- Menghitung posisi aktiva moneter netto pada awal periode
- Menyatakan kembali aktiva moneter netto pada awal periode menurut harga mata uang pada akhir periode.
- Menyetakan kembali penerimaan-penerimaan yang bersifat moneter selama satu periode menurut harga mata uang pada akhir periode.
- Menyatakn kembali seluruh pembayaran yang bersifat moneter selama periode menurut harga mata uang pada akhir periode.
- Menambahkan hasil tahap 2 dengan hasil nomor 3 kemudian mengurangi hasil penambahan ini dengan hasil nomor 4. Hasilnya adalah aktiva moneter netto pada akhir periode menurut nilai mata uang pada akhir periode.
- Membandingkan hasil nomor 5 dengan saldo aktiva moneter netto menurut laporan keuangan akhir periode yang disusun atas dasar harga perolehan historis. Apabila aktiva moneter netto menurut harga mata uang konstan lebih besar dibanding aktiva moneter netto menurut harga perolehan historis, maka diperolah laba. Sebaliknya apabila aktiva moneter netto menurut nilai mata uang konstan lebih rendah daripada aktiva moneter menurut harga perolehan historis, maka terjadi rugi.
Kesimpulannya, keuntungan atau kerugian tingkat harga umum dihitung dengan menyajikan kembali posisi moneter pada awal periode dan transaksi moneter bersih selama periode berjalan sebagai satuan daya beli pada akhir periode. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan posisi moneter bersih aktual, dan perbedaannya menjadi keuntngan atau kerugian tingkat harga umum.
2.1.7 Perbedaan Pos-pos Moneter dan Non-Moneter
Kemampuan untuk membedakan pos-pos moneter dan non-moneter adalah merupakan suatu hal yang penting, karena terdapat perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi kedua jenis pos tersebut Monetary Items adalah aktiva dan kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap misalnya kas, piutang, atau kewajiban lainnya yang jumlah nilai uangnya tetap. Non Monetary Items nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Misalnya Aktiva Tetap, Bangunan, Peralatan, dan Persediaan.
2.1.8 Pilihan Indeks Tingkat Harga
Dua indeks harga yang paling sering diusulkan untuk akuntansi tingkat harga umum adalah Indeks Harga Konsumen dan Deflator Harga Implisit PNB. CPI adalah suatu indeks pembobotan dasar yang dirancang untuk mengukur perubahan-perubahan harga yang terjadi dalam suatu keranjang barang-barang ritel dan jasa yang dibeli oleh keluarga-keluarga berpenghasilan menengah dengan ukuran tertentu yang hidup di pusat kota. Deflator Harga Implisit PNB adalah suatu indeks pembobotan saat ii yang dirancang untuk mengukur perubahan-perubahan harga yang terjadi dalam seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam tahun dasar dari CPI tidak memperhitungkan subtitusi dan barang-barang yang secara relative berharga lebih murah yang terjadi ketika harga-harga relatif berubah. Dengan kata lain, CPI memiliki bias ke atas : kelebihan menyajikan pengaruh dari perubahan-perubahan harga atas biaya hidup. Di sisi lain, pembobolan saat ini dari IPI memiliki bias ke bawah : kurang menyajikan kenaikan harga dalam biaya hidup.
2.2 Kajian Penelitian Sejenis
- David Sukardi Kodrat (2001), meskipun metode General Price Level Accounting lebih interpretative dan relevan namun masih ada masalah tentang cara dan alat untuk menerapkan metode tersebut. Permasalahan tersebut meliputi : cara penyusunan keuangan pada tahun tertentu, dan penggunaan indeks dan masalah penggolongan pos moneter dan pos moneter. Kondisi yang mendesak melakukan penerapan metode (GPLA) adalah tingkat inflasi yang tinggi dan penilaian aset perusahaan.
- Bertha Tampang (2006), akuntansi inflasi dengan metode tingkat harga umum, untuk penilaian rasio keuangan yang lebih akurat. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan konversi ke dalam akuntansi tingkat harga umum.
- Pwee Leng (2000), in conventional accounting, the financial statements prepared on the historical which assumes that prices are stable. If there is a high level of inflation, where inflation is greater than the net rate of return on capital, a large enough number of fixed assets, and working capital turnover is low then the adjustment of financial statements in the general price level needs to be done.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian dalan penulisan ini adalah menggunakan metode General Price Level Accounting (GPLA) dikenal sebagai Akuntansi tingkat harga umum. Unit penelitian yang digunakan adalah PT HM. Sampoerna Tbk, dan unit analisis adalah Laporan Keuangan perusahaan periode 2010 yang telah di audit oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
3.1.1 Profil Perusahaan
Pada tahun 1913, Liem Seeng Tee seorang imigran asal Cina mulai membuat dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya. Perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek maupun rokok putih. Setelah usahanya berkembang cukup mapan, Liem Seeng Tee mengganti nama keluarganya sekaligus nama perusahaannya menjadi "Sampoerna".
Keberhasilan Sampoerna menari perhatian Philip Morris International Inc yaitu salah satu perusahaan tembakau terkemuka di dunia untuk berakuisisi pada tahun 2005. Pada akhir 2010, jumlah karyawan Sampoerna dan anak perusahaan mencapai sekitar 27.600 orang.
Visi dan Misi PT HM.Sampoerna adalah memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. memberikan kompensasi dan lingkungan yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha, dan yang terakhir adalah memberikan sumbangsih kepada kepada masyarakat luas.
3.2 Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan periode 31 Desember 2010,. Laporan keuangan yang akan digunakan antara lain
- Neraca (Balance Sheet) merupakan suatu laporan keuangan dalam akuntansi yang menunjukan keadaan keuangan secara sistematis dari suatu perusahaan pada saat tertentu dengan cara menyajikan daftar aktiva, passiva utang dan modal pemilik perusahaan. Atktiva merupakan harta perusahaan yang tedriri dari aktiva lancar, dan aktiva tidak lancar. Untuk pos aktiva lancar adalah suatu harta perusahaan jangka pendek yang umurnya kurang dari satu tahun sedangkan untuk pos non-aktiva tidak lancar merupakan aktiva yang umurnya melebihi satu tahun. Pada Passiva sendiri terdiri dari kewajiban-kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang serta nilai modal perusahaan.
- Laporan Laba Rugi (Income status) menggambarkan apakah kinerja perusahaan yang ditinjau dalam kurun waktu satu tahun menghasilkan keuntungan dan kerugian, dimana laporan laba rugi ini merupakan kegiatan terhadap aktivitas pendapatan perusahaan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, kemudian dikurangi biaya-biaya operasional dan non operasional.
- Catatan atas laporan Keuangan catatan ini berisi informasi-informasi umum (General Information). Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (Summary of significant Accounting Policies) dan juga penjelasan terperinci dan tiap-tiap akun yang terdapat pada laporan keuangan. Selain data berupa laporan keuangan perusahaan, terdapat juga data berupa Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 1999-2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Pihak yang memerlukan data mengenai informasi PT HM.Sampoerna yang telah dinkonversi menggunakan metode tingkat harga umum adalah pihak eksternal contoh investor dan kreditor karena data tersebut digunakan untuk melihat apakah layak jika mereka ingin menanamkankan modal atau meminjamkan pada PT HM.Sampoerna.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan dua metode Pengumpulan data, yaitu :
- Penelitian Kepustakaan peneliti mencari data sekunder atau informasi-informasi dengan mempelajari buku-buku dan artikel-artikel lain baik dari Koran maupun internet yang berhubungan dengan masalah-masalah dibahas.
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis tabel yang merupakan penyajian pos-pos moneter sebelum dan sesudah konversi dengan menggunakan metode tingkat harga umum (General Price Level Accounting). Selain analisis tabel, penelitian ini juga mengerjakan analisis komparasi dimana membandingkan koom laporan keuangan berisikan pos-pos dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi sebelum penyesuaian berisikan nilai dan masing-masing pos laporan keuangan sebelum dilakukan konversi dengan indeks tingkat harga umum. Kolom faktor konversi berisikan indeks tingkat harga umum sebagai pembanding untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan terhadap adanya perubahan nilai uang. Kolom setelah Penyesuaian berisikan nilai dari masing-masing pos laporan keuangan yang telah dihitung ulang menggunakan kolom faktor konversi.
Proposal ini disusun oleh
Nama : Gania Astried Chaeranny
Angkatan : 2011